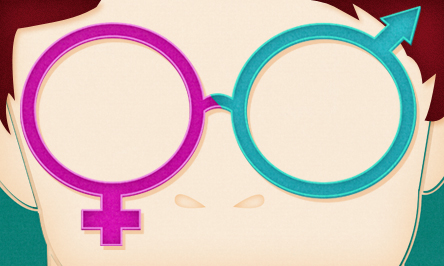Frasa "Itu Karena" yang Selalu Dihilangkan di Iklan
| Thinker |
Iklan televisi tidak menggunakan logika kausatif. Yang ditekankan adalah akibat, bukan sebab. Contohnya sederhana, hanya kita saja mungkin yang tidak ngeh selama ini. Contoh:
Iklan susu formula yang menggambarkan anaknya bernyanyi. Lalu orang-orang disekitarnya senang dan bertepuk tangan.
Akibat: si anak berani bernyanyi di hadapan umum
Sebab: nil
Lalu tanpa dinyana dan dikira, ditayangkanlah merek susu formula. Dibahaslah pentingnya nutrisi bagi si kecil. Alih-alih menggambarkan sebab si anak berani bernyanyi. Yang ditekankan seolah-olah susu formulanya yang membuat demikian. Berani bernyanyi tidak hanya dikontribusi nutrisi saya kira. Peran ortu dan oran sekitar pada ranah psikologis dan afektif anak juga menjadi pendorong.
Jadi, frase 'itu karena' tidak pernah disebutkan dalam iklan. Iklan kosmetik pun demikian. Si A itu cantik bukan karena A itu cantik. Tapi karena produk B, yang membuatnya demikian. Juga dengan iklan provider atau TV kabel pun sama tekniknya. Kalau mau komunikasi lancar bukan karena jaringan bagus. Itu karena ada biaya lagi yang harus ditambah. Iklannya wow, tapi kadang faktanya low.
Adapun dalih 'tapi karena' hilang dengan substitusi 'syarat dan ketentuan berlaku'. Biasanya di iklan cetak banyak dicetak dengan tanda asterik (*). Tanda ini kadang begitu kecil dibawah kata gratis/diskon/sale/promo, dll.
Kadang memang tanda (*) dilengkapi keterangan cukup panjang dan bertele-tele. Yang memang membuat orang yang membacanya malas. Di iklan kosmetik/perawatan tubuh, biasanya ada tulisan kecil di bawah layar. Yang bahkan TV 64 inchi tidak bisa membacanya. Selain samar, keterangan ini mungkin muncul seperseratus detik.
Lalu apa yang menjadi fokus iklan selain produknya adalah feeling. Manusia adalah mahluk virtual. Akan mudah takjub dengan apa yang dilihat. Lalu dirasakan di dalam hati. Saat hati senang, keputusan yang cenderung impulsif dibuat. Keputusan ini biasanya didorong kegembiraan atau sensasi yang dilihat dan dirasa. Tidak heran visualitas iklan akan selalu menarik perhatian. Dalam durasi 15-30 detik kita dibuat terpesona, sedih, tertawa, terinspirasi, dll. Ada perasaan yang distimulasi. Bersamaan dengan ini mereka menyusupi pikir kita 'ini lho produk kami yang bisa bikin pesona, tawa, inspirasi, dll'.
Tanpa sebab yang harus dilihat dan ditelaah; kenapa seorang model bisa cantik, anak bisa sehat, badan pria itu bisa atletis, orang-orang terlihat nikmati makan, dll. Iklan tidak perlu menunjukkan ini. Jika ditunjukkan bisa saja iklan malah jadi film dokumenter. Menjual produk dengan efektif dengan menyentuh sisi afektif adalah kunci. Sehingga keputusan atas dasar sensasi bisa dibuat.
Itu karena menjadi keputusan yang harus kita buat. Logika yang harus benar-benar disadur sebelum kita pergi tidur. Benar tidak anak saya berani bernyanyi karena susu formula? Kenapa Chelsea Islan yang sudah cantik harus didandani untuk iklan produk kosmetik? Apa benar para model pria ber-sixpack itu minum susu biar seperti itu? Apa benar ada jaringan 4G di daerah kaki gunung seperti desa saya?
Artikel lain dari saya:
- Tiga Elemen Pengecoh pada Iklan Produk Kosmetik
- Iklan-iklan Rokok yang Tayang Semaunya (Kembali)
- Menelanjangi Iklan LA Light Cari yang Kerja
Salam,
Wollongong, 12 Oktober 2016